Demokrasi Lokal Dalam Revisi UUD 1945: Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Tak Harus Dipilih
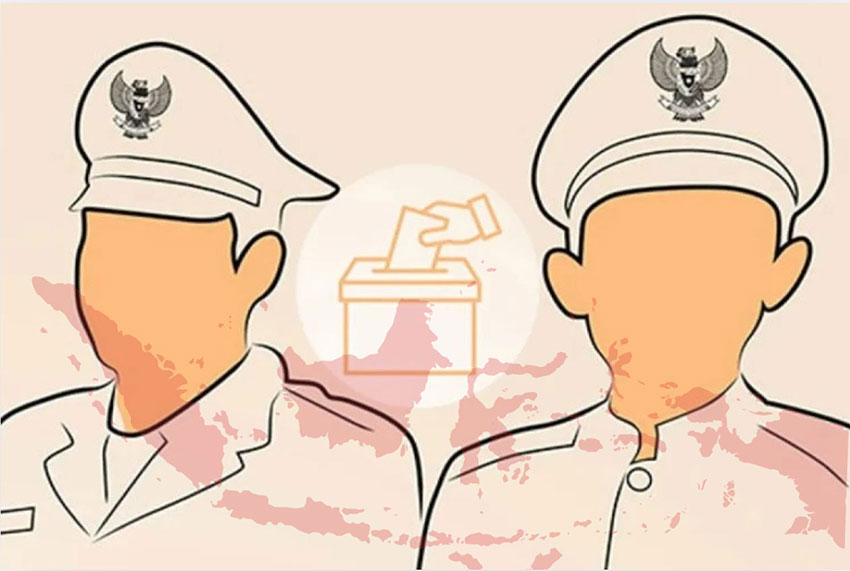
Perdebatan mengenai posisi wakil kepala daerah kembali mengemuka seiring wacana revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem yang berlaku saat ini, kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu paket, dengan legitimasi politik yang sama di mata pemilih. Namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa kesetaraan legitimasi tidak selalu berbanding lurus dengan keharmonisan pemerintahan.
Fenomena “pecah kongsi” antara kepala daerah dan wakilnya pasca-pemilihan menjadi cermin bahwa sistem satu paket tidak selalu efisien, baik secara politik maupun administratif. Revisi UU Pemda kini membuka ruang tafsir baru bahwa wakil kepala daerah tidak harus dipilih langsung bersama kepala daerah, melainkan dapat diangkat berdasarkan mekanisme internal pemerintahan daerah.
Dalam konteks ketatanegaraan, revisi ini menandai pergeseran paradigma dari demokrasi elektoral menuju demokrasi fungsional. Konstitusi tidak secara eksplisit mewajibkan adanya wakil kepala daerah yang dipilih, sehingga pembentuk undang-undang memiliki ruang kebijakan (open legal policy) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan praktik pemerintahan modern. Perjalanan demokrasi lokal di Indonesia tidak pernah berjalan lurus. Ia selalu berbelok, menanjak, dan menurun mengikuti arah perubahan politik nasional, tafsir konstitusi, dan pergulatan kepentingan birokrasi.
Dalam lintasan panjang ¬regulasi pemerintahan daerah, dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tersimpan satu pertanyaan mendasar yang terus bergema hingga kini: apakah kepala daerah harus dipilih satu paket dengan wakilnya, ataukah cukup berdiri sebagai figur tunggal yang mewakili kedaulatan rakyat di tingkat lokal? Pertanyaan ini bukan sekadar masalah teknis dalam pemilihan umum, tetapi juga masalah filosofis dan konstitusional yang menentukan arah demokrasi Indonesia—menyeimbangkan legitimasi populer dengan rasionalitas dalam menjalankan kekuasaan.
Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 memang menegaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Wali¬kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Akan tetapi, teks konstitusi itu berhenti pada kata “kepala pemerintahan daerah”, tanpa menyebut keberadaan wakil. Celah inilah yang menjadi titik bagi beragam tafsir hukum dan politik. Dalam semangat awal reformasi, ketika lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, para perancangnya memahami bahwa yang dimaksud “dipilih secara demokratis” adalah kepala daerah, bukan wakilnya.
Wakil kepala daerah dapat diangkat berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintahan atau kompetensi administratif. Tafsir ini menjadikan posisi wakil kepala daerah sebagai elemen fungsional, bukan simbol legitimasi elektoral. Namun melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, tafsir tersebut bergeser. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur harus dilakukan dalam satu paket.
Dengan begitu, makna “dipilih secara demokratis” diperluas menjadi kolektif: bukan hanya kepala daerah yang dipilih, melainkan juga pasangannya. Perubahan ini mencerminkan transisi dari model “single executive” menjadi “dual executive”, dari tanggung jawab tunggal ke kepemimpinan yang dibagi dua. Demokrasi, dalam tafsir baru itu, dimaknai sebagai proses partisipatif yang melibatkan dua sosok yang dipilih sekaligus oleh rakyat.
Namun, di balik semangat memperluas legitimasi rakyat, kebijakan ini membawa problem baru yang tak kalah kompleks. Pemilihan satu paket kepala daerah dan wakilnya memperbesar biaya politik secara drastis. Setiap kontestasi elektoral membutuhkan anggaran besar untuk kampanye, logistik, alat peraga, dan sosialisasi pasangan calon. Dalam sistem yang mewajibkan dua figur, pengeluaran tersebut otomatis berlipat, baik dari sisi pembiayaan negara maupun dari sisi pengeluaran kandidat.
Di era ketika demokrasi lokal kian mahal, persoalan efisiensi ini menjadi sangat relevan. Demokrasi memang mahal, tetapi tidak berarti harus boros secara struktural. Maka selain persoalan biaya, ada pula persoalan efektivitas pemerintahan. Dalam sistem satu paket, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki legitimasi politik yang sama karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat.
Namun kesetaraan legitimasi itu tidak diikuti oleh kesetaraan kewenangan. Kepala daerah tetap menjadi pemegang otoritas tertinggi, sedangkan wakil kepala daerah hanya bertindak sebagai pembantu dengan fungsi yang terbatas. Dalam praktiknya, struktur ini kerap melahirkan konflik internal yang memecah soliditas pemerintahan.
Kepemimpinan yang dibagi dua mudah tergelincir menjadi persaingan kewenangan, terutama ketika masing-masing pihak memiliki ambisi politik yang berbeda. Dalam banyak kasus di berbagai daerah, wakil kepala daerah bertransformasi dari mitra kerja menjadi pesaing politik kepala daerah pada periode berikutnya. Demokrasi yang semula diharapkan melahirkan kolaborasi justru berubah menjadi arena pertarungan ego dan kekuasaan.
Dari itu dalam sistem yang tidak mewajibkan wakil kepala daerah dipilih satu paket dengan kepala daerah, justru menawarkan alternatif yang lebih efisien dan rasional. Dalam model ini, kepala daerah terpilih dapat menunjuk wakilnya berdasarkan profesionalisme, merito-krasi, dan kesesuaian visi pemerintahan.
Wakil kepala daerah bukan lagi hasil kompromi politik antarpartai, melainkan hasil pertimbangan fungsional yang mendukung kinerja pemerintahan. Biaya politik dapat ditekan secara signifikan, karena pemilihan hanya berfokus pada satu figur kepala daerah. Sistem ini juga memberi ruang bagi stabilitas birokrasi, karena tidak ada risiko perpecahan internal akibat perbedaan kepentingan politik antara dua pejabat terpilih.
Lagian dari sisi hukum tata negara, model non-satu paket ini sebenarnya memiliki dasar konstitusional yang kuat. UUD 1945 tidak pernah menyebutkan bahwa wakil kepala daerah harus dipilih melalui mekanisme yang sama dengan kepala daerah. Artinya, pembentuk undang-undang memiliki ruang tafsir untuk menyesuaikan mekanisme tersebut dengan kebutuhan zaman. UU No. 22 Tahun 1999 dan transformasi Pemilu telah mencontohkan hal ini dengan menempatkan kepala daerah sebagai satu-satunya figur yang dipilih demokratis, sedangkan wakilnya sebagai unsur administratif.
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS
adalah DIRJEN SOSPOL DEPDAGRI RI 1999-2001 DAN GUBERNUR LEMHANNAS RI 2001-2005.
Mantan Gubernur Institut Ketahanan Nasional (LEMHANNAS RI) (2001–2005)
